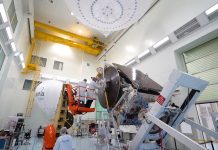“Patut kiranya ada pertanyaan, “siapa hakekatnya yang merasa terancam dengan eksistensi ulama?” Bagi umat Islam di Indonesia, peritiswa Lampung ini bukan yang pertama terjadi.”
Oleh Mabroer MS, Aktivis Nahdliyin
CERITA tentang Ulama tak ada habisnya, khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena ulama di bumi nusantara ini mempunyai andil sangat besar terhadap proses kelahiran NKRI. Bahkan Thomas S. Raffles EIC (1811-1816) mengakui peran sentral ulama dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial yang selalu muncul di berbagai daerah.
Tentu ulama yang mengambil peran itu adalah jenis ulama yang bersendi ilmu yang mencerahkan umat dan perilaku yang terpuji, bukan sebaliknya. Kenapa ada perbedaan jenis ulama? Karena fenomena itu sudah menjadi bagian dari dinamika kehidupan sehingga Imam Ghozali pun jauh-jauh hari sudah memberikan catatan, bahwa, ada ulama baik sehingga patut ditaati dan diteladani perilakunya. Juga ada jenis ulama yang tak layak jadi panutan, apalagi pendakwah.
Diantara catatan emas ulama di Indonesia adalah mereka yang telah mewariskan kisah heroik dalam proses kelahiran NKRI dengan beragam cara. Kala itu, posisi ulama cukup strategis dalam perjuangan memerdekakan umat dan bangsa. Bukan hanya pandai mengajar, tapi juga piawai mengatur perang gerilya melawan penjajah.
Diantara strategi yang mereka tempuh adalah pemilihan lokasi pondok pesantren di berbagai pelosok nusantara sehingga menyulitkan jangkauan kekuatan kolonial. Bang Koko, sapaan eks Rektor Universitas PBB (1980-an) pun mengakui peran ulama tersebut.
Menurut Soedjatmoko Mengoendiningrat, ulama merupakan epicentrum perjuangan kemerdekaan RI karena selalu tampil menjadi ‘imam’ di berbagai suasana, termasuk medan perang gerilya.
Diantara ulama yang cukup populer seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cik Ditiro, Cut Nyak Dien, Fatahillah, kemudian diteruskan generasi berikutnya hingga menjelang kemerdekaan. Misalnya, KH Hasyim Asy’ari (NU), KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), KH Muhammad Natsir, dan masih banyak nama yang patut dikenang atas jasanya meletakkan pondasi kemerdekaan.
Selain ketokohan, tak sedikit para ulama itu pun membangun basis gerakan melalui organisasi seperti yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah (Perti), Al Washliyah, Al Irsyad, Serikat Islam, Mathlatul Anwar hingga ke Timur seperti Al Khaerat yang berpusat di Sulawesi. Semuanya telah menunjukkan dedikasi dan khidmatnya kepada umat sehingga membuahkan anugerah sangat besar yakni kemerdekaan RI.
Namun, peran sentral yang pernah ditorehkan oleh para ulama itu kian tahun terasa makin memudar seiring makin kompleksnya kehidupan yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk fase disrupsi yang dianggap sebagai petaka IT.
Memudarnya daya ingat terhadap peran ulama itu menimbulkan berbagai spekulasi, antara lain pertama, karena ada upaya sistemik untuk menghapus jejak legacy ulama dari buku besar Indonesia dengan beragam interest dan agenda.
Kedua, ada perilaku sejumlah oknum yang menjadikan status ulama sebagai komoditas untuk kepentingan pragmatis. Meski jumlah oknum ini tidak banyak, namun akibat ulah mereka itu justru menjadi ‘nila setitik bisa merusak susu sebelanga’.
Bahkan dalam dekade mutakhir, status ulama tiba-tiba menjadi viral dengan beragam konotasi. Ada yang dijadikan komoditas politik untuk memperkuat barisan kelompoknya, ada juga yang dipakai pengingat agar para pemegang mandat di NKRI tidak lupa diri.
Tapi nurani rakyat akan selalu hidup dan bisa menghirup udara ulama yang masih original dan ulama yang sudah kena polusi. Sebagaimana kita lihat bersama, politisasi status ulama itu grafiknya akan meningkat tajam, jika memasuki fase-fase perebutan jabatan politik seperti pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, pemilihan Walikota hingga pemilihan Kepala Desa. Pada masa-masa seperti itulah ‘harga’ sorban dan tasbih akan berlipat ganda karena diperlukan sebagai kosmetika politik.
Di tengah memudarnya daya ingat tentang peran ulama itulah, kita dikejutkan dengan peristiwa penusukan yang menimpa Syeikh Ali Saleh Ali Muhammed Ali Jaber (44 Th), 14 September lalu saat mengisi pengajian di Bandar Lampung.
Bagi negara, kejadian itu merupakan sinyal kuat adanya korsleting kehidupan kebangsaan di Indonesia, apalagi sebelumnya terjadi hal serupa yang menimpa Jendral (purn) Wiranto selaku Menkopolhukam.
Patut kiranya ada pertanyaan, “siapa hakekatnya yang merasa terancam dengan eksistensi ulama?” Bagi umat Islam di Indonesia, peritiswa Lampung ini bukan yang pertama terjadi.
Bahkan pada 1998-an, darah para ulama juga sempat ditumpahkan secara sadis melalui peristiwa “Santet Banyuwangi” dan operasi “Naga Hijau”. Tragedi yang menimpa sejumlah ulama (NU) Jawa Timur memberikan sinyal yang kuat bahwa Ormas Islam terbesar di Indonesia itu tengah jadi target. Tak kalah tragisnya, para ulama juga pernah memasuki masa kelabu pada tahun 1948 hingga 1965 oleh PKI.
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, upaya mendistorsi peran ulama tempo dulu juga masih berlanjut. Yang lebih fatal lagi, sebagian upaya itu justru dilakukan oleh komunitas internal umat Islam sendiri yang tak sefaham karena mereka datangnya belakangan.
Kenapa? Para ulama pencerah umat dan pecinta bangsa Indonesia itu dianggap sebagai musuh terbesar bagi mereka yang tengah memiliki agenda untuk mengubah ideologi dan dasar NKRI.
Diantara mereka yang sudah terbukti bermaksud mengubah dasar negara itu PKI dan HTI. Keduanya sama-sama berbasis ideologi impor yang sudah kehilangan peminat di luar negeri. Kendati keduanya secara konstitusi sudah dinyatakan tak ada di bumi nusantara, namun denyut keduanya dianggap masih terasa tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan artikulasinya masing-masing. Bahkan tak jarang pilihan gerakan yang mereka gunakan juga acapkali sangat narsis dan kasat mata.
Hanya saja, ada sedikit perbedaan antara PKI dan HTI yakni masa pertumbuhan dan masa kejayaannya. PKI tumbuh subur semasa Presiden Soekarno sehingga memberikan kesan genealogis terhadap kekuatan partai politik yang digawangi oleh keturunan Bung Karno.
Sedangkan HTI justru mengalami pertumbuhan di cukup pesat pada era reformasi, tepatnya semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mengalami benturan keras pada masa Presiden Jokowi karena pencabutan status badan hukumnya HTI.
Perbedaan lainnya, para aktifis HTI piawai mengelola isu keagamaan Islam dengan cover dakwah sehingga berhasil memperpendek irisannya dengan sebagian umat Islam (pro piagam Jakarta). Sebaliknya, PKI justru terjerambab dengan isu-isu non keagamaan sehingga menjadikannya makin dekat dengan isu abangan dan non muslim. Bahkan yang lebih sadis dari ulah PKI itu terekam dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Gestapu PKI).
Yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa isu PKI dan HTI selalu menjadi viral? Kita khawatir bahwa kedua isu tersebut hanya permainan segelintir orang yang tak rela melihat Indonesia melaju dengan mulus menuju Indonesia Emas 2045 mendatang? Maka, dibuatlah mainan yang mudah menyulut emosi umat agar mereka tak disibukkan dengan agenda strategis seperti kemajuan bidang pendidikan, ekonomi, keadilan dan kesehatan.
Kenapa? Banyak pengamat memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu penentu di dunia pada 2045 hingga fase berikutnya. Tentu, capaian itu bisa dilalui jika kondisi sosiopolitik nasional berjalan stabil dan umat Islam sebagai mayoritas bisa jadi teladan. Jika tidak, maka ramalan bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030 itu justru bisa jadi kenyataan. (*)