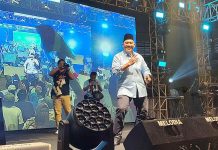Oleh: Suparto Wijoyo*
BEBERAPA ‘jenak’ waktu dalam rentang masa kampanye ini terdapat perhelatan penyelinapan amplop dari tangan sosok yang tengah kuasa dalam segala hal di titik pemerintahan. Begitu yang dimaknai oleh Mispon, kawan yang selama ini sangat kampungan tetapi begitu pas dalam setiap penyeliaan diri terhadap setiap fenomena. Pekan sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap anggota DPR-RI dari Partai Golkar dengan memamerkan 82 kardus serta 400.000 amplop yang berisi pecahan rupiah. Amplop menjadi barang yang sangat dibincang dengan segala aktivitasnya. Imaji publik sekelebatan menembus cahaya uang atasnya. Amplop memang identik dengan uang penanda pesan, apalagi pesan yang dibisikkan dan terekam. Tentu sejumlah 400.000 amplop pastilah dapat diformat dalam sebuah puzzle yang membentuk struktur bangunan gedung DPR-MPR RI. Spektakuler dengan tanda jempol yang sudah diberitakan ke khalayak ramai.
Demikian jua dengan kabar dari Madura. Ada pejabat yang sedemikian teganya memperlakukan guru kaum santri sedemikian rupanya tergambarkan menerima amplop. Sebuah pemandangan yang dalam situasi kampanye pilpres ini seperlirikan dengan kampanye paslon tertentu yang videonya terunggah suka bagi-bagi amplop kepada peserta kampanye. Bahkan ada aparatur penegak hukum yang membagikan amplop di depan orang yang sedang berkuasa sambil mencalonkan diri kembali. Ini semua adalah realitas yang rakyat membacanya semakin risau di tengah bangsa yang dirundung prahara korupsi sesuai dengan OTT KPK terhadap petinggi partai semisal PPP.
Untuk itulah bincangan amplop kadang-kadang menyentuh titik inti korupsi yang saya sorongkan. Hanya saja korupsi di sini bukan yang tidak menjadi kapasitas akademik saya, melainkan yang sejajar saja dengan penyelamatan lingkungan semisal adalah korupsi di sektor tambang. Secara yuridis-ekologis KPK telah memendarkan energi kedigdayaannya dalam memproteksi kepentingan lingkungan di sektor pertambangan dengan membongkar dugaan korupsi Rp 5,8 triliun yang melibatkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi. Sang Bupati ditetapkan KPK sebagai tersangka yang merugikan negara berkenaan dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk sejumlah perusahaan (PT FMA, PT BI, dan PT AIM) saat menjabat periode 2010-2015.
Berdasarkan keterangan pers yang dilansir KPK sebagaimana diberitakan media massa pada 3 Februari 2019 menunjukkan bahwa Timses bupati menduduki posisi direksi dan mendapatkan jatah saham 5% di PT FMA. Kerugian negara yang diungkap KPK melampaui kasus e-KTP (Rp 2,3 triliun) dan kasus BLBI (Rp 4,58 triliun).
KPK terpotret menerapkan perhitungan dalam kerangka valuasi lingkungan yang selama ini menjadi perhatian para aktifis yang gelisah terhadap praktik pertambangan yang destruktif dan polutif. KPK mendata kerugian negara akibat aktivitas tambang PT FMA dari nilai hasil produksi yang diperoleh secara melawan hukum, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan. KPK pun menduga penerbitan IUP eksplorasi kepada PT BI tanpa mengikuti proses yang benar dengan mengabaikan mekanisme lelang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Cacat prosedur ini diyakini melekat pula untuk penerbitan IUP bagi PT AIM sehingga menimbulkan kerugian lingkungan yang cukup besar.
Apa yang diungkapkan KPK tersebut merefleksikan suatu realitas yang selama ini menjadi sorotan publik, khususnya para pegiat lingkungan. Atas nama terobosan hukum demi layanan administratif yang cepat di bidang perizinan, jajaran birokrasi acap kali melakukan terabasan hukum. Mereka mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan berakrobat melintasi prosedur pembuatan keputusan pemerintahan. Prinsip-prinsip good environmental governance yang berupa keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, perlindungan masyarakat adat, dan kepastian hukum “diakali”. Amdal sebagai instrumen hukum untuk melindungi lingkungan dipersepsi menjadi “beban yang bertele-tele” dan bukannya dianggap mandat “tanggung jawab kepedulian” terhadap lingkungan. Saya yakin melalui kasus ini KPK dinanti dapat membuka “kotak pandora” dunia pertambangan yang diwarnai KKN.
KKN ini membawa efek panjang sejenis “simtomatis” (menyangkut tertumpuknya gejala penyakit) yang menderitakan rakyat dan lingkungan teramat serius dari fenomena begitu merasuknya “kekuasaan tambang” ke urat nadi otoritas negara. Khalayak sudah mafhum bahwa pertambangan di Indonesia telah menorehkan tragedi kemanusiaan dan lingkungan di banyak tempat. Ingatlah yang pernah melanda Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara, lahan-lahan bekas tambang di Kaltim, di Papua, bahkan di ujung timur Jawa Timur.
Patutlah diduga adanya hubungan kausal antara derita warga daerah kaya tambang dengan kemiskinan serta tercemarnya lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Mengungkap tabir hukum presumption of causation adalah sesuatu yang esensial bagi peningkatan martabat hukum di Republik ini. Sadarilah bahwa Indonesia adalah negara megakaya bahan tambang dengan kondisi yang diungkap secara satir oleh Carolyn Marr (1993): ”Indonesia is fabulously rich and Indonesia is desperately poor”. Deposit batubaranya mencapai 36.6 miliar ton dan emas 2.650 juta ton. Korporasi pertambangan bertengger dari Sigli-Aceh sampai Tembagapura, Papua. Investor Asia, Eropa, dan Amerika sudah menikmati dengan lahap bahan tambang yang terbentang di nusantara ini. Ironisnya adalah ternyata kekayaan tambang itu tidak otomatis memakmurkan rakyat. Keadaan rakyat sekitar wilayah pertambangan ibarat peribahasa: ”anak ayam mati di lumbung padi”.
Lantas apa makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: ”bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”? Dari langkah KPK saat ini saya menjadi tahu: kalaulah sekarang ada yang menggerus lingkungan, ada yang menambang tanpa reklamasi, ada yang mengambil kekayaan masyarakat adat, ada yang membuat derita dan sengsara, ada warga negara dirundung kemelaratan di daerah kaya tambang, pasti ada tanda-tanda penyakit kronis KKN yang terdiagnosis, meminjam bahasa kedokteran itulah “simtom” korupsi. Semua itu memamerkan parade amplop yang akhir-akhir ini menyematkan anggapan bahwa dalam amplop ada daulat. Itulah titik najis demokrasi yang memuai menjadi demokrasi amplop. Tolaklah.
* Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga