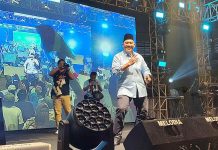“Di sinilah kiranya Nahdlatul Ulama memiliki poin yaitu bagaimana menyikapi ideologi modern yang tidak menggunakan nama Islam yang dituduh sekuler dan mendapat stigma tidak Islam itu.”
Oleh AM Haris Muchid*
TULISAN Arief Afandi pada Ngopibareng mengusung program prioritas Yahya Cholil Tsaquf jika terpilih menjadi ketua umum PBNU ke depan. Yaitu penyebaran faham Islam ala Nahdlatul Ulama ke seantero dunia atau “globalisasi NU”.
Ini sebagai respons dari menyebarnya faham Islam yang menimbulkan tidak hanya friksi, bahkan, dilema sosial-politik hingga konflik berdarah atas nama agama. Aksi yang menelan nyawa hingga ribuan warga sipil ini terjadi seperti di Siria dan Iraq oleh Islamic State of Iraq and Sham (ISIS), Nigeria oleh Boko Haram, dan Afghanistan dan Pakistan yang beberapa tahun terakhir sering terjadi bom bunuh diri oleh oknum jihadis.
Dan, Indonesia yang juga tidak luput dari sasaran bom bunuh diri, baik itu individu, keluarga dan kelompok yang berdalih jihad. Kenyataan pahit ini menjadikan faham Islam ala Nahdlatul Ulama atau sebut saja Islam Nusantara relevan disebarluaskan agar kekerasan atas nama Islam tidak terus terjadi.
Apalagi terbukti, seperti kata Said Aqil Siradj, tidak ada satu pun alumni pesantren NU yang terlibat dalam aksi terorisme. Artinya, bahwa apa yang diajarkan NU benar-benar maslahat dan tidak mengorbankan materi, apalagi sampai memangsa nyawa orang yang tidak berdosa dalam memperjuangkan Islam.
Pertanyaannya: Apakah faham Islam damai atau ramah itu bisa mengglobal? Dalam buku Islam Faces the Modern World, Nissim Rajwan menulis beberapa gerakan Islam yang tidak hanya memiliki ide perubahan besar tapi juga daya dorong luar biasa di era penjajahan Barat atas banyak negara Islam di Afrika dan Asia.
Gerakan tersebut mengusung ide Pan-Islamisme yang mengajak umat Islam sedunia bersatu dan berdaya kuat merebut kemerdekaan. Ide ini melahirkan solidaritas Islam global hingga, kata Ridwan Saidi, di Indonesia terdapat wakilnya Ahmad Surkati yang asal Yaman. Dia mendirikan organisasi Jam’iyah al-Islah wa al-Irsyad al-Islamiyah di Batavia pada 1915.
Kata “Pan” yang mendahului Islam menunjukkan makna lintas batas geografis negara. Artinya bahwa ide ini bersifat global, menyasar semua umat Islam sebagai obyek sekaligus subyek dari ide besar. Selain ini, ide “khilafah” yang mempersatukan umat Islam di bawah satu penguasa juga berkembang seiring dengan tumbangnya kekhalifahan Turki Utsmani pada 1922.
Muncul untuk mewujudkan ide ini secara spesifik Hizb al-Tahrir oleh Tawiyyuddin an-Nabhani di Timur Jerusalem pada 1953. Jauh sebelumnya telah banyak pemikir Islam yang mendukung ide khilafah tersebut termasuk Ikhwanul Muslimin asal Mesir yang berdiri pada 1928.
Organisasi ini merupakan episentrum dari seluruh gagasan besar kebangkitan (revivalisme) Islam abad modern. Berbeda dengan banyak gerakan yang ada, Hassan al-Banna tidak anti kelompok tarekat sufi yang banyak tertolak oleh kaum pembaharu.
Al-Banna bahkan mengatakan bahwa organisasinya adalah kelanjutan dari tarekat Hassafiyah Syadziliyyah, di mana ia menjadi jamaahnya. Salafisme Rasyid Ridho dan puritanisme Wahabi terkoreksi di sini. Al-Banna tidak mau kaum tarekat terserang, meski dia juga memiliki pandangan sendiri tentang tasawuf semacam Tasawuf Modern-nya Buya Hamka.
Al-Banna mengadopsi modernisme Muhammad Abduh, Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani, fundamentalisme dan khilafah Abu A’la al-Mawdudi, Republikanisme Muhammad Iqbal, demokrasi dan ide politik modern lainnya.
Dengan demikian Ikhwanul Muslimin bisa dianggap sebagai gerakan perubahan yang paling holistik dan akomodatif. Jika demikian halnya, mengapa Ikhwan bermasalah dan banyak dilarang di negara-negara Arab seperti Mesir, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab?
Amien Rais dalam disertasi doktornya di Chicago University menyifati gerakan itu dengan Ortodoks Revolusioner. Kata ortodoks karena Ikhwan dalam faham dan tampilan keagamaannya cenderung ortodoks. Sementara revolusioner, karena ia memiliki agenda mengganti penguasa yang ada demi berlakunya faham Islam mereka.
Di sinilah masalah itu muncul, yaitu agenda politik Ikhwan yang laten. Ikhwan seolah tidak pernah merasa berhasil sebelum menduduki kursi kepemimpinan politik. Seolah semua yang memimpin selain mereka adalah kaum sekuler yang memusuhi Islam dan hanya mereka yang benar-benar memperjuangkan Islam.
Kiranya atribut “revolusioner” oleh Amien Rais tidaklah keliru, memang demikian halnya. Di sinilah Ikhwan terus berbenturan dengan pemerintahan mana pun yang tidak menggunakan kata Islam. Ikhwan terjebak pada politik identitas dan klaim kebenaran versi mereka.
Sikap Kiai Hasyim Asy’ari
Di sinilah kiranya Nahdlatul Ulama memiliki poin yaitu bagaimana menyikapi ideologi modern yang tidak menggunakan nama Islam yang mereka tuduh sekuler dan mendapat stigma tidak Islam itu.
Sifat revolusioner yang ingin menggantikan pemerintah dengan dari kelompoknya inilah yang tidak ada dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Bagi NU, kekuasaan adalah sesuatu yang tidak untuk diperebutkan. NU mewarisi tradisi Ahlussunnah wal-jamaah yang menghindari konflik dalam urusan politik.
Hal ini setidaknya ada dalam nasehat Rasulullah kepada Abdurrahman b. Samrah, agar tidak mengharap jabatan. Jika mengharap Allah tidak membantu tapi sebaliknya jika tidak berharap, Allah akan membantu.
KH Adurrahman Wahid atau Gus Dur Presiden RI ke-4 pernah bercerita, bahwa, suatu ketika datang utusan Jepang ke Kiai Hasyim Asy’ari dan bertanya siapa orang Indonesia yang pantas memimpin Indonesia, beliau menjawab: Soekarno. Biarpun Soekarno dari kelompok nasionalis (PNI) dan bukan dari kelompok Islam seperti dirinya, namun beliau tidak segan untuk menunjuk yang bukan dari kelompoknya semata karena yang bersangkutan memang layak dan yang mampu mempersatukan Indonesia.
Beliau tidak mengharuskan dari kelompoknya yang memimpin. Kelompok nasionalis juga tidak dipandang sebagai lawan ideologi Islam. Ia adalah sesama saudara muslim yang memilih menggunakan ideologi modern daripada ideologi agama.
Demikianlah sedari awal Nahdlatul Ulama memposisikan diri tidak terjebak dalam politik identitas dan konflik ideologi. Perkara sosial politik adalah perkara ijtihadiyah yang banyak bergantung pada pertimbangan rasional dan bersifat dinamis tidak kaku.
Berharap pada NU
Oleh karenanya, NU tidak memposisikan diri berlawanan dengan pemerintah yang nasionalis sejauh mereka mampu mewujudkan harapan cita-cita bangsa. Membawa nama Islam dalam politik padahal semua kontestan komit mewujudkan aspirasi Islam, justru akan memonopoli Islam padahal semuanya muslim.
Kedewasaan dalam menyikapi kemelut ideologi inilah keunggulan NU. Dengannya, NU mampu mendampingi Republik Indonesia berdiri tegak di tengah terpaan badai pemikiran dan tingkah polah manusia yang macam-macam.
Tersisa pertanyaan: Akankah keunggulan ini bisa menular lintas negara muslim? Ide kaum revivalis mampu menyebar dengan cepat ke seantero dunia Islam karena menjawab kebutuhan riil dan mendesak yaitu kemerdekaan dari penjajahan Barat atas dunia Islam. Ide itu menjual mimpi kejayaan Islam yang terpuruk 4 abad semenjak era penjajahan. Karenanya ia mendapat sambutan gegap gempita oleh umat Islam. Sementara ide Islam Ramah tidaklah sefenomenal itu. Ia jauh dari sifat revolusioner yang agitatif yang mampu membakar emosi massa.
Untuk itu globalisasi Islam Nusantara perlu mengusung platform-platform yang juga agitatif. Seperti platform Revivalisme jilid 2 setelah jilid pertama tidak kunjung mengantarkan umat Islam dominan di dunia. Revivalisme abad 20 telah berlalu, kini saatnya Revivalisme abad 21,dan NU yang memimpin!
AM Haris Muchid adalah dosen UIN Sunan Ampel Surabaya.