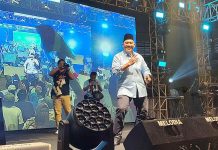”Akumulasi kesulitan yang mencengkeram rakyat jelas wajib dipedulikan pemimpin terpilih. Penderitaan ini tidak boleh dibiarkannya bersemai dan mengakumulasi menjadi kanker ganas….
Oleh: Abdul Wahid*
PEMILU (pencoblosan) sudah usai. Rakyat menaruh ekspektasi besar terhadap pesta demokrasi ini, suatu harapan terhadap terpilihnya pemimpin terbaik yang kehadirannya diabdikan demi kepentingan rakyat, sosok pemimpin yang tidak tergiur dan terjerumus menasbihkan diri dan kelompoknya, tetapi yang benar-benar menempatkan rakyat sebagai subyek yang dilindungi dan selalu dimartabatkannya.
Melindungi atau memperjuangkan nasib rakyat itu memang wajib hukumnya dilakukan sosok pemimpin terpilih, baik dari ranah legislatif maupun eksekutif. Pemimpin ini harus menunjukkan militansi kinerjanya, yang benar-benar ditujukan demi memberikan yang terbaik pada rakyat.
Sebagai sumber historis keteladanan pemimpin terpilih adalah Nabi Muhammad. Beliau menjadi terpilih olehNya diantara para Nabi lainnya, karena hidupnya terfokus atau totalitas dibadikan untuk dan demi rakyat.
Langit ketujuh menjadi puncak ”permintaan” (perjuangan) dan pengabdian yang dilakukan seorang pemimpin terpilih (Nabi Muhammad), yang tentu saja bukan hanya menjadi hak beliau semata, tetapi juga siapapun yang mendeklarasikan dirinya sebagai pewaris model kepemimpinannya, termasuk siapapun yang terpilih jadi pemimpin dalam Pemilu 2019 ini.
“Tak ada kebajikan yang lebih utama setelah iman selain mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, dan tak ada kejelekan yang lebih jelek setelah syirik selain mendatangkan kesusahan (membiarkan penderitaan) pada orang lain”, demikian sabda Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan, bahwa paramater kebajikan utama pemimpin terletak pada aktifitas bercorak ”memproduksi” kebahagiaan sesama, sementara praktik berpola menyusahkan, memproduk kebiadaban, atau memarakkan perilaku ”berkebinatangan”, dikategorikan sebagai ”kejahatan istimewa” (exstra ordinary crime).
Titah itu menunjukkan, bahwa membuat sesama manusia atau rakyat hidup bahagia, senang, aman, damai dan sejahtera merupakan perbuatan kebajikan utama. Manusia (pemimpin) dituntut untuk menunjukkan loyalitasnya kepada sesamanya yang sedang dihadapkan dengan kompilasi deraan ketidakberdayaan seperti ketidakadilan dan penderitaan kemanusiannya.
Kewajiban berpola ”jihad kemanusiaan” (al-jihad al-insaniyah) itu merupakan panggilan setiap pemimpin yang sudah mendaulatkan dirinya dalam panji syahadah politik demokratis (pemilu), suatu pengakuan untuk menyerah total ke hadapanNya, yang menuntut konsekuensi moral-teologis agar kehidupannya tidak dibiarkan vakum dari tanggungjawab mempedulikan rakyatnya.
Kompilasi ketidakberdayaan yang menghegemoni rakyat tidak boleh dibiarkan berlama-lama “menjajah”, tidak boleh ditulikan atau ”dikeringkan” dari hati nuraninya pemimpin, tidak boleh disia-siakan dari tanggungjawab kesejatian profetisnya, serta tidak boleh dianak-tirikan dari kebijakan pembangunan yang bernafaskan keadilan, egalitarianisme, dan kemanusiaan yang diterapkannya.
Akumulasi kesulitan yang mencengkeram rakyat jelas wajib dipedulikan dan didekonstruksi pemimpin terpilih. Penderitaan ini tidak boleh dibiarkannya bersemai dan mengakumulasi menjadi kanker ganas atau penyakit menular yang mematikan, yang sewaktu-waktu atau di kemudian hari dapat meledak dan menghancurkan pori-pori bangunan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Jika penyakit kanker ganas itu sampai tidak direspon secara totalitas oleh pemimpin terpilih, bukan mustahil berbagai bentuk “tragedi nasional” seperti kekacauan, radikalisme dan pertikaian antar etnis akan mengeksplosif dan sulit dalam momentum tertentu. Jika sampai ini yang terjadi, akan terbuktilah kegundahan Napoleon Banoparte, bahwa “di tengah kekacauan yang direkayasa sistemik, maka hanya kaum bajinganlah yang menuai keuntungan dan menikmati kesenangannya”.
Dewasa ini, berbagai jenis penyakit masih menjadi bagian dari wajah konkrit kehidupan manusia Indonesia. Tidak sedikit manusia Indonesia, khususnya yang berasal dari komunitas “akar rumput” (the grass root) yang mengidap penyakit kesulitan menggeliatkan atau memberdayakan dirinya.
Meskipun ini era reformasi dan transparansi, mereka masih belum sukses “memerdekakan” dirinya secara maksimal. Ada kesulitan menyejahterakan diri, ada kegagalan membebaskan kemiskinan, ada duri memendapatkan pekerjaaan yang layak, ada hak melanjutkan pendidikan berkualitas yang belum bisa dinikmati, dan masih banyak yang lainnya, yang kesemua ini, seharusnya bukan mereka saja yang harus memperjuangkan perubahan.
Kondisi itu logis kalau memosisikan negara sebagai yang bersalah atau bertanggungjawab, sehingga siapapun yang nantinya terpilih jadi elemen legislatif atau eksekutif dalam pemilu 2019 berkewajiban menunjukkan kinerja seriusnya. Rakyat mau menggugat pada siapa kalau bukan pada mereka yang sudah dipilihnya.
Tak Bisa Dipandang Ringan
Sebagian elemen bangsa dari akar rumput senyatanya masih mengasumsikan dirinya sebagai korban elitis yang hanya sibuk mementingkan diri dan kelompoknya, sehingga sebagian elemen bangsa masih lekat dengan marginalitas, dan belum meenjadi subjek yang dimanusiakan, disejahterakan atau ”disejarahkan” perlindungan hak-hak utamanya.
Para oknum elitis legislatif (DPRD, DPD, dan DPR RI) misalnya yang terseret dalam penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) seperti korupsi, adalah contoh konkrit kalau pemilu belum memberikan yang terbaik untuk rakyat. Pesta demokrasi ini belum menghasil pemimpin yang membumikan pengabdiannya pada republik ini secara totalitas, dan senghasilkan ”pekerja” politik yang parsialitas atau ambiguitas.
Fakta produk politik demokrasi itu tidak bisa dipandang ringan, pasalnya pagelaran politik yang melibatkan suara rakyat ini sejatinya bagian dari ijtihad politik yang berelasi dengan disain manejemen pemerintahan. Kalau penyelenggarannya tidak menghasilkan pemimpin yang sungguh-sungguh memperjungkan terlaksana atau membuminya amanat ”langit ketujuh” atau suara rakyat sebagaimana diperjuangkan Nabi Muhammad dihadapan Tuhan, maka tidak berlebihan jika pemilunya layak distigma sebagai pagelaran aksesoris demokrasi.
Republik tercinta ini faktanya masih menjadi monopoli segelintir orang yang kepribadiannya merasa imun dari sentuhan reformasi dan bangga bisa “menjagal” hak-hak publik. Negeri ini memang makin kaya dengan sumberdaya manusia, termasuk sosok-sosok manusia intelek (berpendidikan tinggi), namun sebenarnya “tidak cukup cerdas” dalam menerjemahkan dan memperjuangkan kesejatian dan obyektifitas aspirasi rakyat. Ini semua diakibatkan sebagian sosok yang pernah terpilih terseret ”memanjakan” dirinya dalam sindikasi pengkhianatan rakyat.
Dalam ranah itu, rakyat identik kehilangan penyangga yang seharusnya dapat diekspektasikan menjadi kekuatan pembebas atau pemerdeka dirinya dari ketidakberdayaan dan ketidakberdaulatannya. Para pilar strategis bangsa yang idealnya hidup dan berjuang di barisannya, ternyata tereduksi dan bahkan terdegradasi “sense of crisis”-nya atau komitmen pada realitas persoalan kerakyatan atau kebangsaan.
Pemilu kali ini tidak sepatutnya menghasilkan ”destinasi” politik yang marak dengan sosok yang sebatas sibuk membangun dan menikmati “kerajaan” kekuasaan yang didudukinya, dan apalagi sibuk mencari celah-celah untuk menggali dan mendatangkan keuntungan yang bersifat privasi dan kolegial. (*)
Abdul Wahid adalah Pengajar Ilmu Hukum pada Universitas Islam Malang dan pengurus AP-HTN/HAN dan penulis sejumlah buku korupsi.