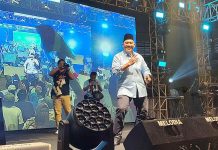Oleh: Suparto Wijoyo*
APA yang terhelat saat ini adalah manivestasi dari kualitas penyelenggaraan negara. Kegaduhan dan kebohongan terus diunggah tanpa lelah sambil menuduh pihak ‘liyan’ yang sejatinya kerap menyuarakan koreksi justru dianggap penghasutan. Dusta dan kepalsuan sering dijadikan berita untuk selanjutnya yang menyuarakan kebenaran dianggap penyebar hoaks. Kondisinya sudah berlangsung nyaris satu “pelita” sehingga ketidakjernihan dianggap lumrah. Air tuba itu dipersepsi sebagai air susu. Minum arak dianggap minum madu. Begitulah yang kerap dibalik-balik dengan jargon keterbalikan itulah kenormalan.
Hasil Pemilu 17 April 2019 sampai melahirkan gerakan ontran-ontran perlu direnungi dengan titik terakhir berupa kesadaran akan kelebat ketidakadilan. Ada ketidakjujuran sebagaimana terlihat selama ini dalam bingkai digital yang sudah amat terang. Pemilu ini untuk memilih pemimpin, pemimpin yang mengerti akan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Pemimpin yang tahu tentang Pancasila, bukan sekadar berteriak Pancasila tetapi lakunya terpotret jauh dari nilai-nilai Pancasila.
Kalau ada pihak di luar golongannya menyuarakan Pancasila dianggap kepura-puraan meski itulah Pancasila yang berkesungguhan secara konstitusional sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Bukan yang lain. Sepertinya ada Pancasila selain dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila di luar tanggal yang ditetapkan sebagai keputusan kolektif pembuat UUD 1945, 18 Agustus 1945 adalah “upaya menjebol kebenaran adanya perjanjian luhur bangsa”. Semua yuris dan para warga negara yang terang kesehatannya berkata mencintai UUD 1945 memahami bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indoensia adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu tidak.
Hal begini atau begitu saja ada yang masih belum paham tetapi kerap meneriakkan dirinya ber-Pancasila. Akibatnya Pemilu jurdil dinodai tanpa mau dikoreksi dan tampil “seperti tidak bersalah” atas hasil-hasilnya. Kedaulatan rakyat ada yang “meniupnya” ke bentara cakrawala sampai tidak berjejak dianggap biasa saja. Kedaulatan itu pun hendak dibuang seperti debu yang melayang-layang setelah “dirampas” dengan segala cara sambil menggunakan kekuasaan. Akhirnya saya mendapatkan pemaknaan dari Cak Mispon yang kerap menjadi kolega berdiskusi mengenai situasi sekarang ini.
Menurut Cak Mispon kondisi yang ada memerikan informasi bahwa yang dipilih adalah penguasa, padahal kita ini ingin memilih pemimpin. Pemimpin pasti mengayomi dan memberikan kehormatan tertinggi kepada kedaulatan rakyat secara jurdil, bukan yang kerap berselongsong intimidasi yang berkelambu manipulasi. Saya bilang kepada Cak Mispon, maaf Cak, ojok begitu, saya khawatir kritik begini dikira membenci. Kalau tidak hati-hati maka menulis opini bisa dibrondong seperti demonstran di Jakarta. Mahkota kekuasaan sudah tidak bisa membedakan mana emas mana loyang, mana rakyat mana penjilat.
Apabila rakyat sampai bergerak tetap dalam pandangan jangan sampai darah tumpah karena mengukuhi kekuasaan. Contoh Gus Dur amatlah nyata. Beliau tidak rela hanya demi jabatan sebagai Presiden untuk berlaku tega membentur-benturkan rakyat, apalagi menumpahkan darahnya. Apa artinya memegang kekuasaan apabila darah sampai membanjiri jalanan. Begitulah yang sangat umum diungkapkan oleh Guru Bangsa, Gus Dur.
Situasi sekarang butuh pemimpin seperti Gus Dur, dan bukan penguasa yang nyaris tidak mau menoleh selain kepada golongannya sendiri, “sekutu-sekutunya” dan yang demo terus didiskreditkan dengan cara menyebarkan ragam pandangan yang menunjukkan kepongahan. Dengarlah suara rakyat yang amat sederhana. Cukup uji forensik komputer KPU, otopsi para petugas Pemilu yang mati, dan hitung manualnya secara bersama-sama para peserta di lapangan terbuka yang dapat diakses semua pihak. Gampang dan amat terang agar tidak sekadar menjadi curiga.
Kenapa membuka data coblosan dengan lampiran C1 plano kok sulit amat dan menimbulkn kesan “kejahatan”. Padahal kesan itu belum tentu benar, sehingga untuk membuktikan kebenaran perlulah keterbukaan dengan jiwa yang jujur. Kalau kekuasaan dikukuhi dengan korban jiwa yang sudah terjadi, belajarlah kepada Gus Dur. Kalau memang engkau mengerti makna dari kepemimpinan sejati.
Kalau penguasa itu berwatak pemimpin niscaya fokus untuk kedamaian rakyat. Mereka tetap tersandar sebagaimana ungkapan sufistik Jan-Fishan:
Kau bisa mengikuti suatu arus
Pastikan bahwa arus itu menuju Samudera
Tetapi jangan kacaukan arus dengan Samudera
Dengan jiwa memimpin (bukan menguasai) dapat terkonstruksi segi tiga pertautan antara demokrasi, birokrasi, dan rakyat secara monumental, yang terbaca dalam sistem semesta. Demokrasi merupakan “matahari” yang memancarkan sinarnya untuk dituang dalam wadah birokrasi yang laksana “rembulan” untuk dipantulkan kembali guna menerangi rakyat sebagai “bumi”.
Tentu saja bumi (“rakyat”) harus diolah (bukan dijarah) dengan kelembutan rembulan (“birokrasi”) yang bertugas memantulkan tanpa henti cahaya matahari (“demokrasi”), dengan tetap memperhatikan garis edar tata surya yang bertaburan bintang-bintang (sebagai pemandu) yang berupa norma-norma bernegara. Hubungan cahaya mencahayai atau pantul memantulkan energi matahari ke rembulan menuju bumi harus dibaca secara siklikal, dan bukan vertikal maupun horisontal agar tidak terjadi penggerhanaan yang dapat menimbulkan keriuhan rakyat.
Di sinilah sejatinya tertambat bahwa rakyat yang menyediakan kesuburan bumi (daulatnya) sudah seyogianya ditata kelola rembulan birokrasi yang mendapatkan percikan cahaya (kuasa) melalui mekanisme demokrasi (pencahayaan matahari). Meski dalam skala relativisme dapat dikatakan bahwa rakyat sejatinya adalah sumber dari segala sumber kuasa birokrasi yang mentransformasikan daulatnya melalui “madrasah” demokrasi.
Spektrum fundamental ini membawa serta kepada ruang bahwa rakyat adalah Sang Daulat. Apa yang dilakukan pemimpin adalah sepernafasan kehendak membangun birokrasi melayani dalam kerangka besar administrative reform yang diperhelatkan. Hal itu merupakan penanda kesadaran untuk selalu ingat pada asal-usul kuasanya, sumber daulatnya. Ibarat air yang mengalir di sungai pada lanjutan kisahnya harus tetap berlabuh di muara luas yang bernama lautan. Itulah kontrak teologis nan asali dan yuridis-ekologis antara birokrasi dalam naungan makna demokrasi untuk memuarakan pelayanan kepada sumbernya: rakyat. Terhadap hal ini saya teringat ungkapan puitis yang dilansir Proklamator Republik Indonesia:
Door de zee op te zoeken,
is de rivier trouw aan haar bron.
Dengan mengalirnya ke lautan,
sungai setia kepada sumbernya.
Sang pemimpin mengingatkan kembali semangat kesetiaan pada sumber kuasa yang mendaulatkan rakyat dengan melayani sepenuh hati. Ketahuilah bahwa rakyat sebagaimana dipermenungkan oleh Pangeran Diponegoro dengan keteduhan hatinya: “mereka ungkapkan hormat dengan segala yang mereka punya”. Kini rakyat hanya punya kedaulatan yang dicoba disuarakan di jalanan Jakarta dan kepemimpinan itu dapat diketahui dengan caranya menangkap pesan demokrasi itu, dengan kebijakan ataukah penindasan.
* Esais, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga