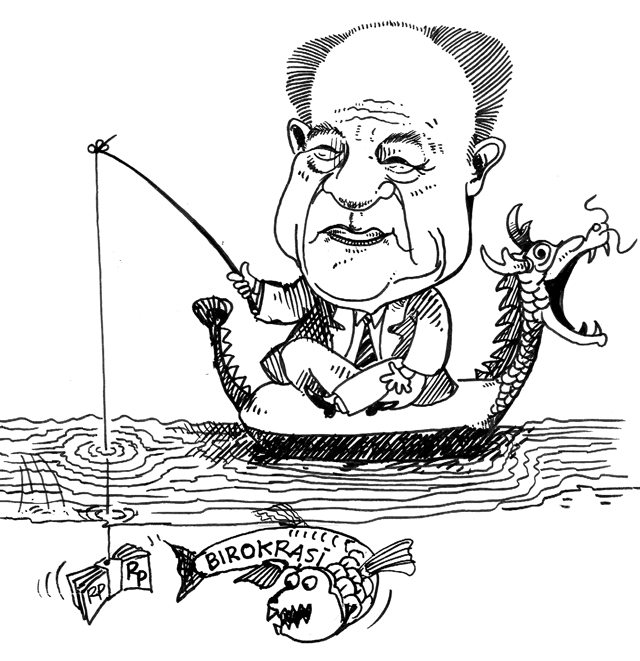
 Oleh: Munawir Aziz*
Oleh: Munawir Aziz*
SUHU politik yang kian memanas di DKI Jakarta, berdampak secara luas di negeri ini. Isu-isu politik yang terjadi di arena kompetisi politik Ibu Kota, merembet ke berbagai daerah dengan varian masing-masing. Media sosial turut membantu percepatan informasi dan silang komunikasi dengan segala tafsiran atas peristiwa yang terjadi.
Namun, yang menjadi catatan penulis, meningkatnya tensi politik di Jakarta, berdampak pada pertarungan dengan segala macam jurus politik dan isu yang ditampilkan. Isu agama, etnis, hingga ideologi politik diolah untuk membentuk citra maupun menghajar opini yang dibangun kelompok lain. Atas nama politik, agama dan solidaritas etnis serta keharmonisan antar kelompok yang selama ini terjaga, menguap ke udara. Keharmonisan tergeser oleh energi kebencian dan sikap curiga. Inikah Indonesia?
Dari konstelasi politik yang ada, selayaknya kita renungkan sikap: bagaimana kebhinekaan yang menjadi ciri khas bangsa ini, dapat terjaga? Bagaimana menguatkan kembali pondasi keharmonisan agar kita tetap menjadi Indonesia? Renungan-renungan dari pertanyaan inilah yang menjadi perhatian penulis saat ini.
Agama dan Kebangsaan
Dalam konstelasi politik mutakhir, agama dan kebangsaan dibenturkan dengan beraneka isu yang diluncurkan dari anak panah politisi. Seolah jurang menganga antara agama dan kebangsaan, antara aqidah dan sikap bernegara. Dalam konteks ini, penulis setuju dengan KH. Ma’ruf Amin (Ketua Umum MUI & Rais ‘Am PBNU) yang menyatakan betapa agama dan spirit berbangsa harusnya berdampingan.
“ Jangan atas nama kebangsaan kita mengorbankan aqidah, namun jangan pula atas nama aqidah kita mengorbankan kebangsaan kita. Aqidah, agama dan kebangsaan harus kita kelola bersama secara baik,” demikian Kiai Ma’ruf mengungkapkan sikapnya dalam beberapa forum yang penulis ikuti. Dalam beberapa sikap, Kiai Ma’ruf memang tegas dalam konteks bernegara dan berbangsa, khsusunya dalam kapasitas sebagai Rais ‘Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Meski, dalam pilihan politik merupakan hak pribadi.
Keprihatinan Kiai Ma’ruf Amin merupakan keprihatinan bersama. Betapa, untuk kepentingan politik, agama diperjual belikan dengan segenap simbolnya. Mereka yang menjual agama di rumah-rumah Tuhan, hanyalah kelompok yang selama ini memahami agama secara politis, untuk tujuan politik tertentu. Sementara, pada sayap yang berbeda, kelompok yang berkeinginan mengusung sikap kebangsaan dengan meremehkan agama, semakin mengeras. Inilah dua sayap kelompok yang perlu didamaikan, agar tidak terbuka jurang yang semakin lebar.
Beruntung, ada kelompok penengah yang tetap konsisten menjaga nilai agama dan kebangsaan. Kelompok inilah, yang selama ini menjaga Indonesia dengan konsistensinya. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dapat disebut dalam kelompok penengah ini. Upaya besar dari tiap penggerak kedua ormas ini, dengan segenap konsekuensi politik maupun manuver yang dilakukan, tetap berada dalam koridor keagamaan dan kebangsaan.
Mengenai kelompok penengah ini, yang dalam pikiran Gus Dur, terayun di antara tradisionalisme dan modernisme, perlu direvitalisasi semangatnya. Gus Dur menganggap revitalisasi tradisionalisme agama sangat diperlukan, dalam bentuk memasukkan unsur-unsur rasional ke dalamnya. Hingga, modernisme agama sendiri dapat dirasakan sebagai kebutuhan, baik di kalangan elitis yang diwakili para cendekiawan, maupun rakyat jelata yang mengembangkan tradisionalisme agama populis.
Lebih lanjut, Gus Dur menilai bahwa, kebudayaan yang diusung sebagai media sekaligus spirit untuk menyebarkan gagasan keagamaan dan kebangsaan, dapat menjadi penopang dari bangsa ini untuk terus menerus mencari identitasnya. Gus Dur menilai, kehidupan beragama kita, yang menjadi penyumbang kebudayaan dalam kebudayaan nasional kita, bagaimanapun haruslah berwatak rasional. Lebih lanjut, Gus Dur menyatakan unsur-unsur yang irasional yang menghambat fungsionalisasi tradisionalisme haruslah diganti dengan nilai-nilai rasional yang akan menjamin kelangsungan tradisionalisme agama (Wahid, 2006: 36-37).
Kelompok penengah (ummatan wasathan) yang tetap setia menjaga garis komando keagamaan dan kebangsaan inilah yang seharusnya didukung bersama. Dengan segenap dinamika internalnya, kelompok penengah ini tetap konsisten menjaga Indonesia, menjaga masa depan NKRI. Bukan kelompok yang menggunakan agama untuk mengusung agenda-agenda politik dan merobohkan konstitusi.
Pondasi terpenting bagi nilai-nilai bangsa, yang terangkum dalam Pancasila, telah dirumuskan secara tepat oleh pendiri negeri ini. Pancasila dapat menjadi rujukan, dengan kontekstualisasi gagasan dan penyegaran terhadap ide-ide yang berkembang dalam ranah nasional-internasional. Namun, yang perlu diwaspadai adalah hilangnya karakter bangsa dan amnesia bangsa ini terhadap identitasnya: kebhinekaan. Dalam catatan Yudi Latif, kehilangan terbesar bangsa ini, bukanlah kemerosotan pertumbuhan ekonomi atau kehilangan pemimpin, namun kehilangan karakter dan harga diri, karena pengabaian semangat dasar bernegara (Latif, 2011: 614). Mengabaikan semangat dasar untuk bernegara, sama halnya merobohkan bangsa ini secara pelan-pelan.
Untuk itu, kita perlu menyegarkan kembali pemikiran keagamaan dan kebangsaan. Keduanya tidak terpisah oleh jarak, namun berkelindan dalam semangat dan makna.
Penulis adalah Dosen di UNIRA MALANG, Peneliti Kaukus Aliansi Kebangsaan.














































