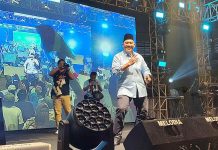“Nah, jika benar yang dikritik (Gus Nur red.) bukan ajaran NU, tapi pengurus PBNU, maka nahdliyin, bahkan dzurriyah muassis (anak cucu pendiri red.) NU sendiri sudah lama melakukan hal itu.”
Oleh: Choirul Anam*
KITA mulai dari keruwetan regulasi. Sejumlah UU, Perpres, Perppu, yang dibuat dan disahkan secara terburu-buru, terutama Omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) yang, oleh Prof Zainal Arifin Mochtar—Pakar Hukum Tata Negara UGM, dinilai sebagai “praktik legislasi ugal-ugalan”. Tanpa mau mendengar dan menerima masukan pihak berkompeten. “Banyak stakeholder yang tidak dilibatkan”, dan meniadakan partisipasi publik. Sehingga, “kelihatan betul UU ini (Ciptaker) dibuat terburu-buru,” kata Prof. Zainal saat bicara di ILC TVOne, pekan lalu.
Kenapa tidak digugat saja lewat JR (Judicial Review) ke MK (Mahkamah Konstitusi)? “Nanti perdebatannya bisa beda lagi. Ke MK itu seakan-akan membiarkan mereka (pemerintah dan DPR) bisa tambah ugal-ugalan. Lalu nanti MK seakan-akan cuci piring. Saya membayangkan itu (proses di MK—red) hanya untuk menghilangkan tanggungjawab pemerintah dan negara,” tandas Prof. Zainal lagi.
Lagi pula, anjuran JR ke MK memang sengaja didengungkan kalangan DPR dan Istana. Bahkan Presiden Jokowi sendiri menganjurkan hal yang sama saat merespon unjuk rasa UU Ciptaker. “Opini itu (JR ke MK—red) sengaja digaungkan pihak Istana dan menjadi agenda settingan mereka,”kata Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru, sambil mengingatkan “harus hati-hati dengan penggiringan opini ke MK, karena ia keluar dari mulut yang sama”.
Baik Prof. Zainal maupun Haris Azhar benar adanya. Masyarakat tak perlu repot-repot JR ke MK. Pasalnya, jauh sebelum pengesahan UU Ciptaker (5 Oktober 2020), pemerintah dan DPR secara diam-diam, pada 1 September 2020, telah merevisi UU tentang MK, dan menghapus Pasal 59, ayat (2) mengenai ketentuan “DPR atau pemerintah segera menindak-lanjuti Putusan MK.” Artinya, menang atau pun kalah di MK, tidak bakalan berpengaruh apa-apa terhadap DPR atau pemerintah. Wow, rupanya sudah diatur secara sistematis bro!
Itulah sebabnya, Ubedilah Badrun, lebih suka menggunakan istilah “kejahatan sistemik yang dibingkai regulasi”. Sebagai akademisi dan mantan tokoh aktivis pergerakan mahasiswa, pendiri FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta), yang menjadi motor penting gerakan reformasi 1998 itu, merasa prihatin dan kecewa terhadap rezim bekuasa. “Rezim eksekutif dan rezim legislatif telah berkolaborasi melakukan kejahatan sistemik yang dibingkai regulasi. Itulah kejahatan besar yang terjadi hari-hari ini,” tandas Ubedilah sebagaimana diurai pada tulisan sebelumnya (Jasmerah 19).
Jika Ubedilah Badrun menyebut pembuatan sejumlah UU sebagai “kejahatan besar yang terjadi hari-hari ini”, Prof. Zainal justru menjulukinya sebagai “praktik legislasi ugal-ugalan”. Karena faktanya, pemerintah dan DPR, seolah menutup mata dan telinga, tak mau peduli terhadap apa yang tengah terjadi di masyarakat.
Pemerintah dan DPR, seolah sengaja memanfaatkan situasi keprihatinan yang mencekam atas serangan Covid-19, guna secepat mungkin meloloskan kepentingannya sendiri. Bukan untuk kepentingan rakyat, karena terbukti suara keras rakyat, dan aksi unjuk rasa hampir semua elemen masyarakat semakin menggelora.
Karena itu, tidaklah keliru jika kini bergerak arus besar suara rakyat yang menyatakan, bahwa sikap abai pemerintah dan DPR terhadap partisipasi publik yang sedemikian itu, bukanlah sikap pemimpin dan negarawan pemegang amanat rakyat yang Pancasilais sejati. Bukan pula pemimpin dan negarawan yang pernah bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh, sebelum mereka memangku jabatan.
Karena itu pula, wajar jika kemudian hasil perbuatannya menuai banyak protes rakyat di mana-mana. Sebab, pemimpin dan negarawan yang abai terhadap suara rakyat, sama halnya dengan mengingkari sumpah janji yang pernah mereka ucapkan: ”akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya, dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
Dan protes rakyat: akademisi, buruh, mahasiswa, pelajar dan elemen masyarakat lainnya, yang disertai demo atau unjuk rasa damai secara besar-besaran itu, janganlah dipahami sebagai tidakan kejahatan atau kriminal. Unjuk rasa damai itu justru merupakan pengorbanan yang tiada tara baik dari segi waktu, tenaga, pikiran, harta bahkan nyawa sekalipun, jika pihak keamanan kehilangan nasionalismenya.
Sebagai pemegang kedaulatan di negara hukum, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, maka unjuk rasa damai itu merupakan jalan terakhir (karena pemerintah dan DPR sudah menurutp mata dan telinga) untuk menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E, ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 24, ayat (1) UU HAM.
Jadi, demo atau unjuk rasa damai itu, hakekatnya adalah untuk menjaga dan mendorong pemerintah dan DPR, agar tetap tegak di atas UUD 1945 dan segala UU serta peraturan yang berlaku.
Karena itu, sangat disayangkan jika kemudian unjuk rasa itu dihadapi dengan kekerasan, menggunakan senjata otomatis dan mengerahkan kendaraan taktis, oleh pihak keamanan—terutama kepolisian. Apalagi ditengarai, sampai ada dua mahasiswa ditembak mati saat demo UU pelemahan KPK, dan banyak pula yang ditangkap saat demo lainnya. Sudah begitu, masih juga ada oknum polisi yang menyamar masuk barisan aksi hanya untuk memancing terjadinya kerusuhan.
Dampaknya, kebebasan sipil terancam karena aparat kepolisian semakin semena-mena. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, mayoritas masyarakat semakin takut mengemukakan pendapat, karena polisi semakin represif.
Survei yang dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling dengan kontak telepon langsung terhadap 1.200 dari 5.614 responden yang dihubungi pada24-30 September 2020, diperoleh hasil 21,9% sangat setuju dan 47,7% agak setuju bahwa situasi saat ini membuat masyarakat semakin takut menyuarakan pendapat.
Selain itu, juga ditemukan hasil 20,8% setuju dan 53% agak setuju mengenai masyarakat semakin sulit menggelar demonstrasi atau melakukan protes saat ini. Juga diperoleh lagi hasil 19,8% sangat setuju dan 37,9% agak setuju, bahwa aparat semakin semena-mena menangkap orang yang berbeda pilihan politik dengan penguasa saat ini.
“Semakin publik menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis, semakin takut warga masyarakat menyatakan pendapat, semakin sulit warga berdemonstrasi, dan aparat dinilai semakin semena-mena, maka kepuasan atas kinerja demokrasi semakin tertekan,”k ata Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Minggu, 25 Oktober 2020.
Tindakan aparat main tangkap, sempat membuat Rizal Ramli, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, berbicara keras di ILC TvOne. “Cara-cara polisi menangkap para aktivis itu sudah keterlaluan, tidak manusiawi, seolah mereka itu teroris. Jumhur Hidayat misalnya, ditangkap oleh 30 personil polisi, pukul 3 pagi dengan dobrak pintu. Istri Jumhur masih pakai night gaun, gak ada waktu buat ganti baju. Jumhur sendiri dalam keadaan luka habis operasi empedu, mau ambil obat saja gak dikasih sama polisi,” kata Bang Rizal.
“Saya sendiri pernah ditahan pemerintah Soeharto, sopan-sopan tuh perwira TNI waktu itu. Kita diperlakukan dengan respect. Sekarang, kalau temannya sendiri, jenderal polisi, tidak diborgol. Sementara mahasiswa dan para aktivis diborgol. Taipan-taipan brengsek seperti Djoko Tjandra, bebas lepas begitu saja,” kata Rizal Ramli sembari menambahkan “dulu yang memperjuangkan agar polisi dipisahkan dari TNI adalah Gus Dur, Pak Mahfud dan saya. Maksudnya supaya polisi menjadi kekuatan pengayom rakyat. Dwifungsi ABR kami hapuskan”.
Tapi, kenyataanya, hari ini TNI sudah tidak dwifungsi, justru polisi yang multifungsi. “Anggarannya 125% dari tiga angkatan dan kelakuannya itu, mohon maaf deh. Aktivis itu bukan teroris, dan tidak akan bikin kapok dengan cara ditangkapi seperti itu. Apa dikira kapok? Enggak! Teman-temannya makin melawan. Jangan gitulah. Ini zaman sudah merdeka, apa mau kembali ke sistem fasis,”tandas Bang Rizal bernada tinggi.
Meski mayoritas rakyat menilai aparat semakin semena-mena, tetapi, masih ada pihak yang justru memuji kesigapan dan kecepatan aparat kepolisian dalam merespon laporan dugaan tindak pidana. Misalnya, Sekjen PBNU dan Ketua Umum GP Ansor yang memuji aparat kepolisian, terkait penangkapan Sugi Nur Raharjo alias Gus Nur, pada Jum’at (24/10/2020) dini hari, di rumahnya, di Malang.
Gus Nur ditangkap oleh penyidik Ditsiber Mabes Polri, dengan dugaan melanggar pasal UU ITE tentang “Penyebaran Kebencian dan Bermusuhan berdasarkan SARA dan Pencemaran nama baik”.
Sepanjang diketahui publik, Gus Nur bukan mengkritik NU sebagai jam’iyatu adlin wa amanin, wa ihsann wa ishlahin—sebagaimana dawuh hadratus syaikh KH Hasyim Asy’ari dalam Muqaddimah Qonun Asasi. Tapi yang dikritik Sugi Nur, seperti banyak beredar di medsos, adalah pengurus PBNU. Terutama pengurus PB hasil muktamar NU ke-33 di Alun-Alun Jombang, Agustus 2015. Bukan barang baru.
Nah, jika benar yang dikritik bukan ajaran NU, tapi pengurus PBNU, maka nahdliyin sendiri sudah lama melakukan hal itu. Dan PBNU pimpinan Prof KH Said Aqil Siraj (Kiai SAS) mestinya legowo dan berjiwa besar dalam menghadapi segala macam kritikan.
Mengapa? Karena, mulai dari proses sampai dengan hasil muktamar NU ke-33 itu, dari sudut pandang mana pun sulit untuk dikatakan sebagai “Muktamar Nahdlatul Ulama”. Tapi lebih tepat disebut “Kongres Parpol” yang penuh kegaduhan dan sarat manipulasi data dan peserta.
Selain itu, para petinggi PBNU sendiri telah mendeklarasikan NU sebagai Ash-habul Qoror—penentu kebijakan atau bersahabat dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Bahkan Khitthah NU yang telah dirumuskan dengan susah payah oleh para ulama besar NU dalam Muktamar ke-27 di Situbondo (Desember 1984) sebagai dasar pijakan NU, justru dimaknai mutaghoiyrah atau kondisional, tergantung pada perubahan situasi dan kondisi politik zamannya.
Akibatnya, pasca muktamar, terjadi mufaraqah dari berbagai pengasuh pesantren besar baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah lainnya. Lalu muncul NU Garis Lurus yang digawangi ulama muda, KH. Luthfi Bashori dan KH. Idrus Romli. Disusul lagi dengan terbentuknya KKNU’26 (Komite Khitthah Nahdlatul Ulama 1926) yang diprakarsai para dzurriyah muassis—anak keturunan pendiri NU (genetis maupun ideologis), terutama oleh al-maghfurlah KH. Sholahuddin Wahid (Gus Sholah).
Dan kini, KKNU’26 dipimpin Prof. Rahmat Wahab dan Gus Sholahul Aam Wahib, yang karena keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi kebangsaan dan kenegaraan saat ini, mereka bergabung sebagai presidium KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) bersama Prof. Din Syamsuddin dan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.
Saat ini sudah ribuan kiai dan pesantren yang bergabung dalam KKNU’26. Belum lagi para ulama muda yang berada di bawah naungan NU Garis Lurus. Apakah semua itu perlu dlaporkan polisi agar supaya ditangkapi?
Atau, dalam suasana keprihatinan masyarakat dan bangsa terhadap berbagai UU, terutama UU Ciptaker, yang menciptakan aksi demo besar-besaran hingga saa ini, NU lebih baik mengaktifkan lagi Kanal Youtube NU Channel dengan short movie bukan hanya film “MY FLAG MERAH PUTIH VS RADIKALISME” yang menggerkan umat Islam? Untuk apa ini?
Apakah tabi’at santri NU memang seperti yang tergambar dalam film itu? Apakah dengan film itu, nama NU menjadi semakin harum? Dan apakah jika banyak orang mengritik film “kemproh” itu, berarti mencemarkan nama baik NU? Lalu dilaporkan polisi dan ditangkap seperti Sugi Nur? Mengapa kita tidak mawas diri? (bersambung).
*Choirul Anam, adalah Pendiri dan Penasehat PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah). Pembina GERAK (Gerakan Rakyat Anti Komunis) Jawa Timur.