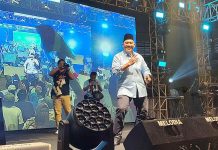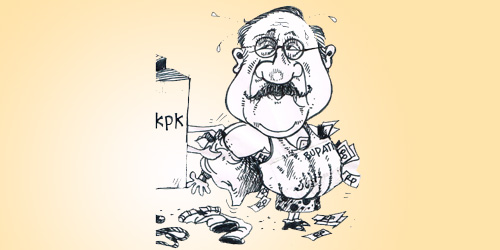
 Oleh Munawir Aziz*
Oleh Munawir Aziz*
GELOMBANG kelompok politik yang menggunakan simbol-simbol keagamaan semakin mengeras dan meruncing. Kekuatan politik ini, berusaha mengambil untung dari polarisasi publik, keterbelahan masyarakat dan jurang sentiment etnis. Letupan-letupan konflik sosial, yang berhembus dari kontestasi politik, berpotensi menjadi konflik yang meluas di masyarakat kita. Meski konflik dan ujaran kebencian (hate speech) masih berembus di media sosial, namun efek kebencian terasa berdampak pada interaksi antar personal di ruang publik.
Kenyataan ini menjadikan kita semakin tersungkur pada politik kebencian dan duka nestapa karena pertikaian. Narasi kebhinekaan yang selama ini menjadi perekat persatuan, dipecah belah dengan tujuan untuk membuat garis demarkasi antar kelompok warga. Inilah politik kebencian yang mengggunakan agama sebagai pemicunya, serta itu etnis sebagai pelontar konflik selanjutnya.
Sementara, masjid-masjid menjadi arena pertarungan kepentingan dengan khotbah-khotbah dan majlis pengajian yang memproduksi pandangan politik. Bukan politik kebangsaan, namun politik kebencian yang menunggangi agama. Jika kita melakukan kunjungan singkat di beberapa masjid di Ibu Kota Jakarta, akan terlihat bagaimana politisasi tema-tema khotbah yang didesain untuk membentuk persepsi publik. Tidak jarang, narasi kebencian yang tampil di panggung agama ini, menimbulkan ketidaknyamanan.
Meringkus kebhinekaan
Setelah komodifikasi isu-isu dan simbol keagamaan, yang kemudian berlangsung adalah komodifikasi kebencian dengan menggunakan isu etnis. Pembenturan antar etnis, merupakan langkah picik sekaligus sadis, untuk merusak pondasi kebhinekaan bangsa ini. Jika selama ini, founding fathers bangsa Indonesia, membangun persatuan dengan kesadaraan perbedaan-kebhinekaan dari etnis, agama dan adat, maka inilah identitas bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Kebhinekaan menjadi kesadaran untuk merawat persaudaraan dan kesatuan.
Namun, jika ada kelompok politik dan (calon) pemimpin yang menggunakan kebhinekaan sebagai piranti untuk memecah belah bangsa, maka inilah politik kebencian yang berbahaya. Jika pemimpin melupakan prinsip-prinsip kebhinekaan, dan hanya mengejar persatuan dengan keseragamaan, maka dampak panjang yang timbul hanyalah politik diskriminasi.
Prinsip-prinsip kebhinekaan telah diringkus oleh kepentingan politik yang menggunakan jubah agama. Narasi kebhinekaan ditikam oleh gerakan Islamisme, yang mengambil manfaat dari sentimen agama seraya memompa kebencian dari kelompok-kelompok libtas agama. Kita menyaksikan, betapa Islam dan non-Islam telah demikian mengeras dan meruncing perbedaannya, dari yang sebelumnya sebagai saudara dalam ikatan bangsa Indonesia.
Gerakan Islamisme yang mengkomodifikasi agama, harus dilawan dengan gerakan keislaman—dan keagamaan—yang berprinsip menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembenturan antara agama dan bangsa, antara Islam dan keindonesiaan, harus dihindari dengan pembalikan wacana yang menyelaraskan Islam dan kebangsaan, agama dan keindonesiaan kita.
Islamisme, menurut analisa Bassam Tibi, cenderung menggunakan agama sebagai kendaraan politik. Dalam karyanya, Islam and Islamism (diterjemahkan menjadi “Islam dan Islamisme”, Mizan 2016), Tibi mengungkap bahwa gerakan Islam politik secara eksplisit berusaha memperluas ajarannya ke seluruh dunia. Islamisme, mengubah universalisme Islam menjadi internasionalisme politik, yang berusaha menggantikan tataran sekuler yang ada, dari negara-negara berdaulat dengan satu Islam. Pada tahapan selanjuynya, Internasionalisme Islamis menawarkan ummah bentukan (invented ummah).
Islamisme di Era Post-Truth
Bangsa Indonesia sedang dalam ujian kontestasi politik yang mewartakan kebencian. Inilah ujian panjang bagi warga negeri ini, dalam kapasitasnya sebagai bangsa besar yang majemuk dan memiliki pondasi kokoh berupa Pancasila. Nilai-nilai keindonesiaan, keadilan, kesetaraan, kebangsaan dan kemanusiaan yang tumbuh dari kesadaran berbangsa, berakar dari pemahaman yang menyeluruh atas prinsip Pancasila. Namun, prinsip-prinsip ini, terus mendapat ujian di era pasca kepercayaan ini.
Menurut William Davies, kolumnis The New York Times, kita masuk pada zaman politik pasca kepercayaan (an age of post-truth politics). Menurutnya, ketika dunia sudah terdominasi sedemikian kuatnya oleh pencitraan dari televisi maupun media-media yang dibangun dengan konstruksi iklan, realitas-realitas yang ada semakin hambar. Di dunia pasca kepercayaan ini, populisme menjadi senjata utama yang berkolaborasi dengan strategi media sosial. Sementara, publik menginginkan apa informasi yang hendak dikonsumsi, dengan menentukan sendiri media-media dan sumber yang dibaca. Di era ini, pemimpin-pemimpin yang populer menentukan alur wacana.
Populisme yang terbentuk oleh strategi kampanye massif di media—baik di media konvensional maupun media sosial berbasis digital—berusaha membangun persepsi publik. Nalar publik dibentuk dengan narasi, data, argumentasi yang dikonstruksi dengan pesan, nilai dan ideologi yang telah terintegrasi dengan kepentingan politik. Inilah era pasca kepercayaan, yang menantang para pemimpin kita untuk terus mengaktulisasi gagasan dan gerakan. Jangan sampai, kebhinekaan kita diringkus oleh Islamisme, jangan sampai ikatan persaudaraan sebagai bangsa, dihancurkan oleh kepentingan politik yang menggunakan amunisi kebencian .
*Peneliti Aliansi Kebangsaan, Dosen UNIRA Malang.