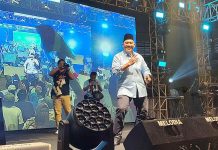Oleh: Munawir Aziz*
Momentum politik dalam rangkaian Pilkada DKI Jakarta menyajikan beberapa pelajaran berharga. Selain sebagai pendewasaan dan pematangan politik bangsa Indonesia, proses Pilkada juga memberikan pesan tentang politik identitas dan bahaya komodifikasi agama.
Sebagai ajang kontestasi politik yang menentukan konstelasi politik nasional, Pilkada DKI Jakarta menjadi bukti betapa alat-alat politik yang digunakan untuk berkampanye melebihi batasan-batasan yang selama ini terjadi. Politik etnis, isu rasial hingga cemoohan terhadap etnis tertentu santer terdengar tiap hari. Hal ini menimbulkan efek psikologis dalam memori warga, sekaligus– dalam rentang panjang– dampak pembalasan atau reaksi politiknya. Kebencian antaretnis semakin mengeras.
Pada titik tertentu, strategi politik yang digunakan menggunakan klaim-klaim agama untuk merebut simpati. Kita bisa mendengar dan menyimak, bagaimana masjid-masjid di DKI Jakarta seperti terbakar amarah. Terbakar amarah? Ya, khotbah-khotbah di beberapa masjid, sejauh yang saya temukan dan saya cek ulang ke banyak teman, sebagai wajah Islam di Jakarta pada masa kini. Tentu, ini bukan klaim sepihak, yang harus dibuktikan dengan riset-riset yang lebih detail dan interdisipliner untuk melihat gambaran lebih komprehensif.
Namun, sepanjang yang saya pahami, apa yang terjadi di DKI Jakarta menjadi alarm bahaya tentang bagaimana komodifikasi agama dapat memecah belah warga. Sebelumnya kita menyimak tentang penolakan salat jenazah di tempat ibadah, oleh kelompok tertentu hanya karena beda pandangan dan prinsip politik.
Lalu, beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta diusir ketika salat Jum’at. Bayangkan, seorang muslim diusir dari masjidnya oleh muslim lainnya. Ini bukan pembelaan terhadap pasangan calon tertentu. Bukan, bukan tujuan saya memberi tempat untuk aspirasi politik pada tulisan ini. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana melihat betapa kebencian telah demikian mengeras.
Politisasi Masjid
Apa yang terjadi di DKI Jakarta harus menjadi pelajaran bersama. Bahwa, komodifikasi agama menimbulkan bahaya yang efeknya panjang. Politisasi masjid menjadikan tempat ibadah bukan lagi sebagai oase untuk penjernihan spiritual, namun sebagai ruang pergerakan politik praktis. Sebagian masjid-masjid di DKI Jakarta telah terbakar amarah, hingga berkobar dendam dan kebencian.
Lalu, apa yang dapat dilalukan, agar kondisi mengerikan ini tidak meluas? Tentu saja, dibutuhkan mental negarawan, karakter pemimpin bangsa. Yang dibutuhkan tidak sekedar politisi yang ingin jadi pemimpin, dengan akrobat kata-kata atau caci maki. Namun, yang dibutuhkan bagi bangsa ini lebih pada pemimpin bangsa yang bergerak dengan nurani.
Pemimpin yang mencintai bangsanya, yang berpikir visioner, tidak akan rela masyarakatnya menjadi bahan bakar kebencian. Pemimpin seperti itu tidak akan mau kemenangan politiknya diraih dengan ‘membakar’ rumah ibadah dan menenggelamkan kemanusiaan.
Selain itu, untuk meredam politisasi masjid, perlu membentengi pengurus/takmir masjid dan khatib-nya dengan semangat kebangsaan. Prinsip kebangsaan yang dipadu dengan keinsyafan beragama, akan melahirkan cara dakwah yang santun dan segar. Sekaligus, tidak membiarkan masjid-masjidnya sebagai kendaraan politik untuk mengkampanyekan program politik praktis.
Masjid-masjid seharusnya menjadi ruang untuk membumikan pesan-pesan Allah, untuk syiar keislaman dengan cara yang damai, amar ma’ruf bil ma’ruf. Masjid bukan ruang kompetisi politik, namun untuk persatuan umat Islam melalui kekhusyukan ibadah.
Semoga masjid-masjid di negeri kembali sejuk dengan tumbuhnya spiritualitas umat, bukan kebencian dan amarah.
*Penulis aadalah Peneliti Aliansi Kebangsaan, Dosen di UNIRA Malang.